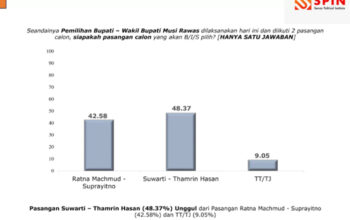Oleh : KOMPOL. SURYADI, SIK, M.H.(Serdik Sespimmen Dikreg Ke – 61 Tahun 2021)
Saat ini Indonesia nampak hendak memasuki situasi dimana kepercayaan public (public trust) kepada berbagai stakeholder penegakan hukum semakin rendah. Dapat dilihat bagaimana persepsi masyarakat melihat hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata justru sebaliknya. Efektivitas penegakan hukum dirasa hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang sekedar melakukan tindak pidana ringan (tipiring).
Sementara itu, pelaku kejahatan besar seperti koruptor (KKN) yang biasa disebut kejahatan kerah putih (white collar crime), sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini, dibutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
Hukum yang berlaku dalam masyarakat, tebang pilih, bergantung dengan kelas sosial dan kemampuan finansialnya. Orang yang berada pada stratifikasi sosial atas jelas mendapat perlakuan yang berbeda (privilege) dengan orang yang berada pada stratifikasi sosial yang lebih rendah (middle low). Orang yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau posisi yang lebih tinggi, mendapat perlakuan khusus atau kehormatan khusus dari pada orang yang berasal dari latar belakang keluarga biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau posisi dalam masyarakat. Artinya, di sini posisi hukum yang berlaku ada indikasi ketidakadilan. Hukum yang tajam ke bawah dan hukum yang tumpul ke atas.
Padahal idealnya penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkupnya masing-masing, dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang ingin dicapai.
Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum itu ditegakkan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi, organisasi penegakan hukum juga semakin
kompleks dan sangat birokratis.
MENGAPA BISA BEGITU ?
Kajian sistematik penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu: perangkat hukum, aparat penegak hukum, warga masyarakat yang dipengaruhi oleh ruang lingkup peraturan hukum, faktor budaya atau budaya hukum, sarana dan prasarana. faktor fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan undang-undang. (Soerjono Soekanto, 1983 : 15).
Hikmahanto Juwono (2006) menyatakan bahwa di Indonesia secara tradisional, lembaga hukum yang melaksanakan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat. Di luar lembaga tersebut, masih ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lembaga sektoral lainnya.
Jika kita amati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik danmasih cukup memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum selalu cenderung dinamis dalam interaksi antara aspek hukum idealita (das sollen), dan aspek penerapan hukum dalam realitas (das sein).
Realitas penegakan hukum yang demikian pasti akan melukai hati ‘rakyat kecil’ yang akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, terutama pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan terhadap praktik suap, membuat hukum di negeri ini justru bisa diperjualbelikan, seperti kasus BLBI yang titik tolaknya masih belum jelas, kasus E-KTP yang melibatkan banyak pihak, dan beberapa kasus besar lainnya yang telah terhenti. Melihat kondisi tersebut, nampaknya kita harus merenungkan kembali tujuan akhir dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan.
Konsep hukum yang berkembang saat ini merupakan kelanjutan dari hukum yang bertumpu pada kekuasaan politik yang sentral. Soetandyo (2013) melihat pergeseran ini dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu ketika hukum berlandaskan moralitas yang terjadi sebelum zaman penjajahan, kemudian terjadi transformasi pada masa penjajahan, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukum kolonial kemudian dikembangkan dan diajarkan
di Indonesia (sekolah hukum).
Kemudian terjadi seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2010), yaitu sistem lama yang notabene liberal, telah menimbulkan “penyakit” tersendiri, sebagaimana juga banyak dikritik di Amerika Serikat. Di Indonesia, dalam konteks pemberantasan korupsi, sering dikatakan bahwa pengadilan telah menjadi tempat yang aman bagi para koruptor.
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum memang dimulai dari teks (hukum), tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Teks hukum yang bersifat umum memerlukan ketelitian atau penajaman kreatif bila diterapkan pada peristiwa nyata di masyarakat. Pada akhirnya, apakah supremasi hukum dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, tidak bergantung pada bunyi pasal-pasal hukum, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak melampaui panggilan tugas.
Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu menganggap serius hak dan melakukan pembacaan moral terhadap hukum. Ditilik dengan teks baru merupakan awal dari perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar hukum dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia.
Menurut Himahanto (2006), permasalahan dalam penegakan hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, antara lain: 1.Permasalahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 2. Masyarakat yang mencari kemenangan bukanlah keadilan. 3. Uang mewarnai penegakan hukum. 4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh. 5. Sumber daya manusia yang lemah. 6. Advokat tahu hukum versus Advokat tahu koneksi. 7. Keterbatasan anggaran. 8. Penegakan hukum dipicu oleh media massa.
Permasalahan tersebut di atas memerlukan solusi, dan negara yang diwakili oleh pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang memadai sementara output mereka pada perlindungan warga negara diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sebagai sejauh mungkin dapat menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
MENYADARI PERAN KEPOLISIAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum. Berbagai perkembangan teoritis mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan di atas, tidak hanya akan mempengaruhi kinerja kepolisian, tetapi juga harus diantisipasi. Baik pada tataran perumusan, aplikasi maupun eksekusi di lapangan. Posisi strategis Polri dalam hal ini terkait dengan konsepsi teoritis bahwa polisi adalah “gatekeeper” dan “goal prevention officer” dari sistem peradilan pidana. Polisi adalah penjaga gerbang sistem peradilan pidana.
Setiap kali seorang penjahat “berhubungan” dengan hukum pidana, biasanya Polisi yang pertama menghadapinya. Hal ini sesuai dengan desain prosedur sistem peradilan pidana yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang akan terus bergulir ke sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen Kepolisian. Dalam hal ini, apakah perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat tergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai penyidik dan penyidik.
Fungsi Polri dalam penegakan hukum tidak semata-mata sebagai fungsi represif, tetapi juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja kepolisian tidak hanya diisi dengan upaya mencari fakta pendukung tentang kesalahan faktual dan menemukan tersangka, tetapi juga aktif melakukan pencegahan terhadap segala potensi yang dapat mengarah pada kejahatan. Hal ini semakin krusial mengingat fenomena kejahatan yang semakin kompleks.
Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan kejahatan, harus steril dari kepentingan golongan, atau kepentingan politik, termasuk segala tantangan baru kejahatan sebagaimana tersebut di atas, berada di tangan Polri.
Oleh karenanya, penting untuk menuntut kemerdekaan atau independensi Polri agar ; pertama, untuk menjamin terselenggaranya pencegahan dan penindakan kejahatan semata-mata demi penegakan hukum (pro justitia). Dengan kata lain, kemerdekaan Polri mengarah pada penegakan hukum yang bebas dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi tertentu, tetapi hanya dalam rangka mewujudkan kebijakan negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Kedua, independensi menjamin efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, karena independensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan profesionalisme Polri. Dalam hal ini, independensi memungkinkan Polri untuk menentukan secara akurat dan dengan kekuatan maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Ketiga, independensi Polri dapat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Dalam hal ini, kewenangan hukum sedikit banyak tergantung pada tingkat pengungkapan kejahatan oleh Polri (clearance rate), yang jika cenderung positif akan semakin menjamin kepastian hukum (enforcement). Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang saat ini disinyalir semakin menurun. (legal culture).
Oleh karena itu, sangat diharapkan semua stakeholder penegakan hukum, utamanya Kepolisian yang menjadi the gate keeper of criminal justice system dapat mengilhami tugas pokok dan fungsinya secara ideal dalam realitas sosial masyarakat yang sangat multikultural dan banyak benturan kepentingan, sehingga pada akhirnya dapat menegasikan munculnya public distrust secara massive dan luas.